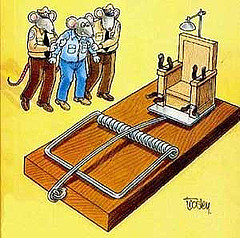“Hanya keledai yang jatuh lebih dari sekali di lubang yang sama“. Nukilan adagium ini relevan untuk menyingkirkan pikiran agar Kejaksaan membuka kembali kasus BLBI. Merupakan kenyataan yang hampir tak mungkin dibantah, Kejaksaan telah gagal mengusut BLBI. Buruknya dan rendahnya komitmen internal kejaksaan masih tetap menjadi persoalan mendasar penanganan kasus korupsi di Indonesia, khususnya BLBI.
JURANG GELAP SKANDAL BLBI
Dimuat di: Koran Tempo, Kamis 27 Maret 2008
Silang sengkarut skandal korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) seperti berada di bibir jurang. Setelah proses hukum obligator BLBI tersendat-sendat hampir 10 tahun, Kejaksaan Agung justru menghentikan penyelidikan BLBI yang melibatkan Samsjul Nursalim dan Anthoni Salim (28/2). Tiga hari berselang, publik dikejutkan kabar tertatangkapnya UTG, Ketua Tim Jaksa BLBI dalam dugaan suap Rp. 6 miliar.
Ditengah tingginya perhatian publik untuk mengungkap BLBI, Mahkamah Agung justru mengurangi hukuman salah seorang obligator BLBI, David Nusa Wijaya hingga 4 tahun pidana. Ketidakpercayaan sekaligus kekecewaan publik telah bertumpuk. ICW mencatat, putusan ini adalah salah satu bentuk ketidakberpihakan pengadilan umum terhadap agenda anti korupsi.
Secara makro, lemahnya komitmen pengadilan umum dalam kasus korupsi dapat dilihat dari trend putusan tahun 2005 hingga 2007. Sebagian besar hakim memutus bebas atau menerapkan pidana minimum terhadap terdakwa korupsi. Di tahun 2005, lebih dari 75% putusan dikategorikan tidak berpihak pada agenda anti korupsi, dengan perincian 41% diputus bebas, dan 34,6 % dihukum pidana minimal kurang dari 2 tahun. Fenomena ini tidak berubah secara mendasar hingga tahun 2007.
Seperti catatan ICW, bahkan di tahun 2007 putusan bebas mencapai angka 56,8%, dan hukuman minimal sejumlah 15,2%.Dari catatan ini dapat dibaca fenomena krisisnya pemberantasan korupsi jika masih ditangani pengadilan umum. Atas dasar itulah, korupsi BLBI sebagai sebuah mega skandal yang merugikan rakyat ratusan triliun rupiah harus dijauhkan dari prosedur yang berujung pada pengadilan umum. Di titik inilah, dorongan agar KPK mengambil alih dan proses hukum dilaksanakan pada pengadilan Tipikor harus disikapi serius.
Jika dicermati, inilah putusan yang kesekian kalinya menafikan aturan hukum fundamental. Hakim secara tegas telah mengacuhkan kewajibannya. Bab IV undang-undang kekuasaan kehakiman mengatur tiga pasal mendasar tentang kewajiban hakim. Disebutkan, ”hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (Pasal 28 ayat 1)”, dan ”dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan sifat baik atau jahatnya terdakwa (ayat 2)”.
Semangat anti korupsi pada putusan Kasasi sebelumnya juga disingkirkan dengan alasan hakim kasasi tidak memperhatikan itikad baik terdakwa.
Selain melalaikan kewajiban untuk mengikuti rasa keadilan masyarakat, hakim pun memelintir ketentuan Pasal 28 ayat (2) UU kekuasaan kehakiman. Seolah ingin dikatakan, pidana terhadap terdakwa harus dikurangi karena ia telah bermaksud baik mengembalikan aset. Tapi, tidakkah pengembalian aset adalah kewajiban yang seharusnya dituntaskan secara sukarela sebelum adanya proses hukum? Kenapa terdakwa tidak menuntaskan? Bukankah pengembalian pasca diadili justru merupakan bentuk tidak beritikad baiknya terdakwa? Karena hal tersebut dilakukan atas dasar keterpaksaan. Seperti diketahui, David baru mengembalikan sebagian kecil aset setelah proses hukum berjalan.
Selain itu, David pun tidak menghargai supremasi hukum ketika memutuskan kabur (buron). Seharusnya, ketidaktaatan ini jadi catatan memalukan bagi MA sebagai penjaga keadilan, bukan justru menjadi alasan peringan bagi terdakwa.
Disebutkan diatas, hakim PK dapat dikatakan menafikan kewajibannya ”menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. Kemudian, memelintir makna kewajiban ”memperhatikan sifat baik dan jahat terdakwa”. Dua hal ini diatur pada Pasal 28 UU 4/2004, Bab tentang ”Hakim dan Kewajibannya”.
Pada bab yang sama dicantumkan juga sumpah dan janji hakim untuk memenuhi kewajiban dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Dan, pelanggaran terhadap sumpah dapat menuai konsekuensi serius. Hakim agung dapat diberhentikan tidak dengan hormat jika melanggar sumpah atau janji jabatan (Pasal 12 ayat (1) UU Mahkamah Agung). Apakah para hakim berpikir tentang konsekuensi ini? Sebaliknya, apakah Mahkamah Agung berani menjalankan tugasnya untuk mengusulkan pemberhentian hakim bermasalah yang melanggar sumpah jabatan?
Kembali pada pertimbangan hakim PK yang menilai hakim kasasi salah menerapkan hukum karena menggunakan UU 31/1999. Bagian ini harus diakui selalu menjadi perdebatan. Di satu sisi, pihak tertentu akan mengatakan sebuah undang-undang tidak boleh berlaku surut. Atau, untuk perbuatan BLBI yang terjadi di tahun 1998, tidak dapat digunakan undang-undang yang ada di tahun 1999.
Untuk hal ini, mungkin hakim PK benar. Tetapi, tidakkah ada asas yang mengatakan, aturan yang baru mengesampingkan aturan sebelumnya? Sehingga, UU 31/1999 dapat menjadi salah satu bagian pertimbangan dalam memutus perkara BLBI. Kecuali, jika hakim kasasi hanya menggunakan UU 31/1999 sebagai dasar putusan. Seperti diketahui, hakim kasasi hanya mengambil semangat dari undang-undang yang baru untuk menjatuhkan pidana bagi terdakwa. Karena saat proses persidangan, telah juga terjadi perubahan aturan hukum yang sekaligus berarti peningkatan semangat anti korupsi.
ambil alih
“Hanya keledai yang jatuh lebih dari sekali di lubang yang sama“. Nukilan adagium ini relevan untuk menyingkirkan pikiran agar Kejaksaan membuka kembali kasus BLBI. Merupakan kenyataan yang hampir tak mungkin dibantah, Kejaksaan telah gagal mengusut BLBI. Buruknya dan rendahnya komitmen internal kejaksaan masih tetap menjadi persoalan mendasar penanganan kasus korupsi di Indonesia, khususnya BLBI. Sehingga, dorongan publik agar KPK mengambil alih penting disikapi.
Persoalannya, apakah KPK jilid II ini punya komitmen mendorong pemberantasan korupsi? Jika ya, KPK harus menentukan sikap untuk menangani BLBI. Atau, kalaupun KPK menolak, harus dijelaskan alasan yang rasional bagi publik. Bukan semata argumentasi retroaktif yang bahkan telah dibantah berulangkali oleh banyak akademisi dan ahli hukum. Karena publik tidak ingin, skandal BLBI ini jatuh dalam jurang yang gelap dan hening. Sebuah kengerian, BLBI yang tersungkur di ”Grand Canyon” yang tak berdasar. (*)
Febri Diansyah